Kapan?
Apa yang unik dari lebaran? Tradisi bermaaf-maafan, makan lontong-opor-sambal goreng, mudik (yang sempat tertunda dua tahun)... apa lagi?
Yap, pertanyaan kapan.
"Kapan lulus?"
"Kapan nikah?"
"Kapan punya anak?"
"Kapan si kakak dikasih adik?"
(Eh, tapi enggak ada, tuh, yang nanya, kapan mati?)
Semua pertanyaan itu terasa wajar bagi generasi orang tua kita, atau sebagian besar masyarakat kita yang tradisional, yang menganggap pertanyaan itu adalah bentuk perhatian dan kepedulian. Sayangnya, tidak demikian bagi kalangan modern atau milenial, yang menganggap pertanyaan itu bersifat pribadi yang jawabannya tidak perlu diketahui orang lain.
Ngomong-ngomong soal pertanyaan yang bersifat pribadi, saya sempat lihat twit yang isinya kira-kira begini: Kalau semua pertanyaan dilarang ditanyakan dengan alasan privasi, lalu bahasan apa yang tepat ketika berbincang dengan orang? Masa iya, biar aman, ganti tanya, "Buku sekolahmu dulu terbitan Erlangga atau Tiga Serangkai?"
Sepertinya, kok, ada gap antara generasi terdahulu dengan generasi kini soal masalah ini, ya? Yang satu bersifat sosial, terbuka, kordial; yang satu cenderung individualis. Masalahnya, polarisasi ini bersifat ekstrem. Pihak satu merasa berhak menanyakan sampai pada hal yang di luar kuasa manusia, misalnya pertanyaan kapan punya anak. Pihak yang lain sedemikian sensitif, sampai pertanyaan 'sudah lulus atau belum' dibalas dengan mempertanyakan kontribusi si penanya terhadap pendidikannya Mungkin, memang perlu ada pengertian antara satu pihak dengan lainnya.
Bagi saya sendiri, pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah sudah lulus, sudah nikah, sudah punya anak, anaknya ada berapa, dan lain-lain itu sebenarnya tidak masalah. Yang ditanyakan memang kabar, supaya tahu kondisi terkini si kerabat atau kenalan. Kan, sudah lama saudara atau teman ini tidak lama bertemu, dan jarang berkomunikasi di waktu-waktu lainnya.
Enggak lucu, kan, kalau suatu saat kita ketemu teman lama, dia gandeng anak kecil, terus kita tanya, "Eh, ini anak siapa?"
Atau, kita lagi kirim undangan, terus di kotak penerima tertulis, "Saudara A dan istri." Eh, padahal dia belum nikah. Apa enggak malah tambah nyesek, tuh? Dikira kita lagi nyindir, padahal enggak tahu beneran.
Atau, berkaitan dengan tradisi bagi-bagi angpao, biasanya anak/keponakan yang sudah kerja "tidak dianggap" alias tidak perlu diberi angpao, terlepas dari berapa pun umurnya. Ketika itu, si anak tersebut tidak dikasih angpao, sementara saudaranya yang seumuran atau lebih tua dikasih. Apa iya, dia enggak bakal mbatin atau ngerasani? Ya, gimana... tadi ditanya sudah kerja atau belum malah melengos!
Pertanyaan-pertanyaan tadi seharusnya tidak masalah. Tidak perlu baper, apalagi kalau yang tanya orang tua atau kerabat yang lebih sepuh. Tak perlu menjawab dengan sinis, apalagi pasang tarif, hehe....
Hanya saja...
Saya sepakat jika pertanyaan basa-basi ini perlu dibatasi. Cukuplah ketika yang ditanya menjawab sudah atau belum, si penanya merespons jawaban tersebut dengan, "Oh, begitu," dengan menampilkan wajah datar. Cukup tahu, gitu aja.
Yang membuat situasi jadi kurang nyaman, ya, pertanyaan lanjutannya.
"Kok belum lulus?"
"Kok belum kerja?"
"Kok kerjanya di rumah, bukan di kantor BUMN?"
"Kok belum nikah? Kapan nikah?"
"Kok belum punya anak?"
"Kapan si kakak mau dikasih adik?"
Dan serangkaian "kok" atau "kapan" lain yang kesannya malah mempertanyakan takdir Allah.
(Yaa... menurut ngana, sini enggak pengin tahu jawaban dari "kapan" itu juga?)
Yang lebih menyesakkan lagi, pertanyaan itu masih berlanjut dengan membandingkan dengan "capaian" orang lain.
"Si A sudah lulus S-3, lo, kamu D3 aja enggak kelar-kelar."
"Si B sudah jadi bos BUMN, kamu masih jadi karyawan start up aja."
"Si C sudah punya 5 anak, kamu mikirin nikah juga enggak."
"Coba tanya tips ke si D, baru nikah tiga bulan, udah langsung hamil. Enggak kayak kamu, lima tahun enggak hamil-hamil."
Pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya di luar kuasa manusia begini, ini, yang bikin orang sering kufur nikmat.
Yang tadinya seseorang sudah ikhlas menjadi jomlo fisabilillah, dia berubah sedikit "genit" menarik lawan jenis biar dibilang "laku".
Yang tadinya seseorang sudah menerima bahwa takdirnya seperti Bunda Aisyah yang tidak dikaruniai keturunan langsung, dia mulai mempertanyakan keadilan Allah.
Pertanyaan soal "kapan" ini memang sedikit tricky. Penanya harus sadar, kapan boleh ditanyakan, kapan enggak. Yang enggak boleh ditanyakan, seperti yang dijelaskan di atas, kalau ini berkaitan dengan takdir Allah, yang bagaimana pun usaha manusia, kalau belum rezekinya, ya enggak bakal terjadi.
Terus, yang boleh yang kayak apa, dong?
Yang masih bisa diusahakan manusia; yang tertunda karena ulah manusia itu sendiri.
Misal, "kapan nikah" kalau dia jelas-jelas udah mampu nikah tapi masih luntang-lantung sama lawan jenisnya (eh, kalau ini, mah, belum mampu nikah pun tapi kerjaannya nempel terus, dosa juga, sih, wkwk). Kan, beda, ya, dengan pertanyaan serupa yang ditujukan pada orang yang belum punya calon—gimana bisa menjawab kapan nikah kalau calon aja belum punya?
Tapi, ya... tetap lihat-lihat situasi, sih. Seberapa dekat si penanya dengan yang ditanya? Seberapa tahu tentang peristiwa-peristiwa lalu yang mengikuti kejadian tersebut? Dan aspek-aspek lain yang nanti bisa nyambung juga ke fikih dakwah, tapi itu bahasan lain lagi.
Apakah kita bertanya itu karena beneran ingin tahu jawabannya sebagai bentuk kepedulian? Apakah kita kasih saran itu benar-benar ingin memberikan solusi atau sekadar biar dianggap bijaksana?
Berdirilah di tengah-tengah. Yang bertanya, tanyalah seperlunya. Kalau yang ditanya enggan menjelaskan lebih jauh, jangan mendesak. Dia enggan menjawab juga belum tentu karena jawabannya bersifat rahasia, tapi kadang susah untuk dijelaskan. Yang ditanya pun jangan gampang baper, tanggapi aja dengan senyuman dan muka tembok. Anggap aja itu karena mereka care dengan caranya sendiri.

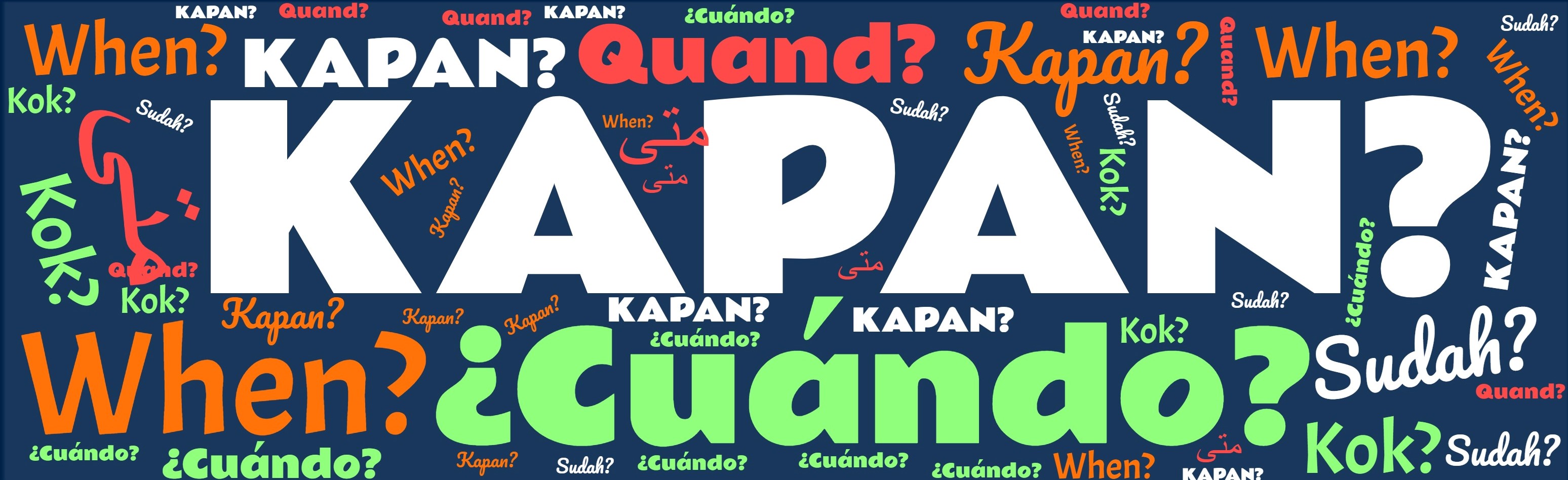



No comments